Cerita ini juga dimuat di Reader's Digest Indonesia Website dan menjadi artikel pilihan editor periode keempat.
Pantai.
Mendengar satu kata itu terbayang debur ombak yang
memecah di tengah lautan. Pasir-pasir halus yang tersapu air laut. Atau
burung-burung yang beterbangan menuju sarangnya. Aku selalu mencintai
pantai dan keindahannya. Dan awal tahun ini aku mendapat kesempatan
untuk mengunjungi salah satu pulau terbaik yang pernah aku kunjungi,
yaitu Phillip Island, terletak di sebelah tenggara kota Melbourne,
Australia.
Pukul lima sore aku berangkat. Dengan jarak tempuh
sekitar 140 kilometer, butuh waktu sekitar dua jam untuk menuju ke sana
menggunakan mobil. Aku pergi ke sana dengan seorang saudaraku yang sudah
lama tinggal Melbourne. Dari kejauhan, aku sudah bisa melihat laut
terhampar, beradu dengan sinar matahari sore yang memantulkan sinar di
permukaannya.
Untuk memasuki area Phillip Island, mobil kami
harus menyebrangi jembatan sepanjang sekitar 1 kilometer yang
menghubungkan area Phillip Island yang terpisah dari daratan Australia.
Pulau yang cukup luas ini memiliki berbagai macam tempat wisata dan
kegiatan yang berhubungan dengan alam, mulai dari pantai, area surfing,
kemping, bersepeda, hingga melihat-lihat kekayaan alam Australia. Di
Phillip Island juga, kita bisa menemukan Penguin yang pulang ke
sarangnya pada saat senja tenggelam. Undeniably cute!
Walau
Phillip Island memiliki banyak pantai, seperti Shelley Beach, Summerland
Point, dan Woolamai, waktu itu aku hanya mengunjungi dua tempat selama
berada di sana, yaitu The Nobbies dan Penguin Parade karena tujuan
utamaku memanglah untuk melihat Penguin. The Nobbies terletak di sebelah
ujung barat pulau Phillip, merupakan sebuah tanjung yang langsung
menghadap laut. The Nobbies memiliki kontur yang berbukit-bukit dan
memiliki boardwalks yang membawa wisatawan berjalan-jalan di sekitar.
Karena di antara bukit-bukit tersebut, terdapat banyak sarang Penguin
dan burung pantai! Langsung deh, aku menjepret kamera begitu sang
Penguin kecil muncul dari sarangnya. Dan di bawah bukit tersebut,
terhampar langsung laut yang ombaknya memecah di antara batu karang.
Begitu romantis, apalagi di kala sunset dan ditemani sang pacar (yang
sayangnya tidak pada saat itu).
Sekitar pukul delapan malam
(which is, yang masih sangat terang benderang karena pada musim panas
matahari tenggelam pada pukul 9 malam), aku dan saudaraku beranjak
menuju Penguin Parade. Di Penguin Parade, kami membeli tiket “khusus”
untuk menonton para Penguin yang baru pulang dari laut setelah berburu
ikan. Biasanya mereka muncul pada saat sunset dan datang berombongan
memasuki sarangnya. Sayang, kami tidak diizinkan untuk menangkap gambar
apa-apa selama di sana, tidak juga dengan kamera HP.
Kami berdua
duduk di sebuah tribun yang langsung menghadap ke pantai, persis seperti
orang yang mau menonton konser. Di samping kanan-kiri kami banyak turis
yang berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Sekeluarga tulis Latin
duduk di depan kami, sementara di samping kami sepasang suami-istri
berwajah Asia Timur duduk dengan mesranya.
Aku menatap jauh garis
cakrawala di depan. Angin yang berembus semakin lama semakin kencang
hingga aku harus merapatkan jaket. Bahkan aku men-double-nya dan angin
masih saja ganas menusuk tulang-tulangku. Pada saat itulah aku merasa
seperti sedang benar-benar sendiri.
Aku menatap garis cakrawala
itu, menyadari bahwa tempatku berasal ribuan mil jauhnya berada di
baliknya. Aku membayangkan hangatnya suasana rumahku saat itu, di mana
aku biasanya bertemu orang-orang yang aku cintai. Sekarang, aku berada
di sini. Kedinginan dan sendiri. Di sebuah tempat asing yang tak kukenal
sama sekali. Indah... Namun terasa menyakitkan. Aku merasa seperti ada
yang hilang. Aku seperti kehilangan kebahagiaanku. Ketika melihat
orang-orang di sekitarku bersama orang-orang terkasihnya, aku justru
berada sangat jauh dari mereka semua. Aku harap aku bisa menemukannya.
Menemukan mereka dalam sekejap mata.
Dan di saat matahari
tergelincir di ufuk barat, di saat rombongan Penguin berpulang ke
sarangnya, aku menyadari sesuatu yang membuat mataku terasa panas. Aku
ingin pulang. Ke tempat di mana orang-orang yang kucintai berada.
Senja
di Phillip Island ini membuatku belajar bahwa, tak peduli seindah apa
pun tempat yang kukunjungi, tempat terindah adalah tempat di mana aku
hidup bersama orang-orang yang kucinta. Seperti Penguin yang sepanjang
hari berburu ikan di laut, pada akhirnya mereka akan kembali ke
sarangnya masing-masing bersama sesamanya yang mereka kasihi.
Sunday 16 December 2012
Saturday 25 August 2012
Seribu
Setengah berlari, aku melepaskan tas lusuh yang kusampirkan dan membantingnya begitu saja ke atas kursi. Tas tersebut adalah milik ayah yang beliau turunkan kepadaku. “Masih bisa dipakai,” katanya, meski telah bolong di sana-sini dan terpaksa ditambal berkali-kali.
Rumah masih terasa lengang. Ayah masih betah di sawah, sementara adikku si Aski badung itu pasti sedang mementas layangan di lapangan. Meskipun begitu, tetap saja rumah ini terasa sesak. Rumah yang sangat pantas untuk disebut gubuk ini hanya memiliki 3 ruangan utama: kamar keluarga, ruang tamu, merangkap dapur dan ruang makan, kamar Bapak dan Ibu, dan kamarku dan Aski. Tak ada jendela-jendela besar seperti milik orang gedongan, yang ada hanyalah lubang ventilasi lembab untuk sekedar mengintip dunia luar.
“Pelan-pelan loh, Nduk,” Ibu yang sedang menjahit di meja kerjanya mengomentariku. Tangan dan kakinya anteng menggerak-gerakkan mesin jahit tuanya yang usang. Aku tidak mengindahkan ceramah beliau kali ini. Aku bergegas menuju kamar dan mempersiapkan diri.
Setelah lulus sekolah hampir setahun yang lalu, tetes demi tetes keringat kucurahkan agar mimpiku tidak hanya berhenti sampai di sini. Tidak hanya berhenti sebagai kuli panggul yang pekerjaannya tiap hari menggotong karung beras. Tidak hanya sekedar memiliki ijazah SMA yang tertumpuk debu di lemari. Biar miskin begini, jangan salah, aku adalah salah satu lulusan terbaik sekolahku tahun lalu. Hanya saja nasib memang membenturku karena lembaran sakti yang harus dengan susah payah kukumpulkan demi bisa meneruskan sekolah: uang.
Satu tahun sudah cukup kuhabiskan membanting tulang, merendahkan kepalaku di hadapan orang-orang, dan menjadi kacung yang bisa dioper ke sana ke mari. Hari ini sudah kucukupkan semua itu. Aku tak mau lagi menjadi orang rendahan. Aku tak pernah merasa terhina hanya karena aku miskin. Tetapi aku terhina jika aku bodoh.
Hidup di desa terpencil yang jauh dari peradaban bukan halangan untuk membuka duniaku menjadi lebih lebar. Di saat banyak teman-temanku yang putus sekolah dan berakhir menjadi kacung seperti orang tuanya, aku bersikukuh untuk menamatkan SMA-ku meski aku harus menambah beban kedua orang tuaku. Di saat banyak orang yang masih terbelenggu dari dunia selain desa Tegalgundul yang bahkan di peta pun tak nampak, aku berusaha mencari akses agar aku bisa mengintip dunia luar yang dikatakan banyak orang itu mahaluas.
Internet. Aku mengenal istilah internet beberapa bulan lalu dari Pak Kepala Desa saat aku berkunjung ke kantornya. Kebetulan Pak Ahmad—namanya—adalah kenalan Bapak semenjak beliau masih kecil. Mereka berdua dulu adalah teman sepermainan dan sering mementas layangan bersama. Keadaan ekonomi keluarganya yang cukup berada mengantarkannya menjadi kepala desa, sementara ayahku tetap menjadi seorang petani miskin yang hanya bisa menghidupi keluarga kecilnya.
Satu bulan yang lalu, saat aku sedang bosan dan bermain ke kantornya Pak Ahmad, beliau meminjamkanku komputernya dan membiarkanku memenuhi hasratku akan rasa ingin tahu tentang dunia luar. Kantor Pak Ahmad adalah satu-satunya bangunan yang bisa dikatakan “beradab” di desa ini. Tembok semennya bersinar dicat berwarna putih, lantainya mengilap yang selalu dipel setiap hari, dan perabotnya tertata rapi di dalam ruangan. Jauh berbeda dengan rumah bambu kami yang usang.
Kota besar... Jalan raya... Sekolah... Universitas... Anganku melayang-layang, membayangkan dunia utopis di luar sana. Dunia fana yang kadang membuat terlena, namun sudah kurindukan untuk berjumpa. Hingga kutemukan sebuah informasi tentang pendaftaran mahasiswa baru di salah satu universitas negeri ternama.
Inilah kesempatanku. Seolah ada secercah sinar harapan yang menyergap, bergegas aku kembali ke rumah mengendarai sepeda ontel Bapak, warisan dari Mbah dan Mbah Buyut dari zaman perang, kata beliau. Mau benar atau tidak, pokoknya sepeda ini dengan secepat kilat mengantarkanku kembali ke rumah. Secepat kilat mengantarkan informasi itu ke telinga Bapak.
Sesuai dugaanku wajah Bapak merengut dan alisnya naik satu. “Sekolah? Kan kamu sudah tamat sekolah,” jawab Bapak tak acuh sambil menyeruput kopinya.
“Maksudku, aku pengen kuliah, Pak,” balasku, tak merasa terintimidasi oleh nada keraguannya.
“Kuliah?” suara Bapak mulai meninggi. “Kuliah opo thok, Fri. Kamu kira di kampung ini punya tempat kuliah seperti yang kamu bilangin itu?”
“Makanya aku pengen ke Jakarta, Pak,” jawabku lirih, bukan karena takut emosi Bapak akan meledak, tetapi karena tidak ingin Ibu mendengar suara Bapak yang marah-marah.
“Jakarta?” Bapak bertanya lagi, seolah semakin tidak mengerti dengan omonganku yang ngawur. Beliau meletakkan cangkir kopinya di atas meja dan menatapku lekat-lekat. “Wis, jangan ngimpi loh, Fri. Mendingan kamu kerja sana, cari duit, biar bisa makan . . .” Bapa bangkit bersiap meninggalkanku sebelum aku sempat membalas.
“Pak!” aku memanggilnya sebelum Bapak masuk ke kamar. Bapak berbalik dan kutatap mata bingungnya. “Afri serius pengen kuliah, Pak.”
Bapak kembali mendekat dan berdiri di hadapanku. Mata sayunya itu telah menunjukkan perjalanannya selama ini, kepedihannya, ketegasan di balik sikapnya, bahkan kelembutan yang tersirat dari sorot matanya bisa kulihat secara bersamaan.
“Fri, orang kecil seperti kita ini gak perlu mimpi muluk-muluk . . .” suara Bapak berubah merendah, dengan nada halus yang jarang sekali kudengar. “Kalau kamu mau jadi kepala desa seperti Pak Ahmad, atau jurangan beras seperti Engko Liam, Bapak dukung. Jangan, jangan mimpi kejauhan, Nduk, Bapak takut kamu jatuh,” Bapak menggelengkan kepalanya sambil menepuk pundakku pelan.
Lampu minyak yang remang-remang menerangi wajah Bapak menyadarkanku bahwa Bapak hanya mau membawaku dalam kenyataan yang ada. Potret kehidupan kami yang selama turun-temurun diwariskan. Potret sebuah keluarga petani miskin yang hanya bisa menghabiskan harinya dengan bermimpi. Bermimpi punya lahan yang luas. Bermimpi punya hasil panen yang banyak. Bermimpi bisa memiliki uang berlimpah. Bahkan sampai mimpi-mimpi sesederhana itupun tak jua dapat terlaksana. “Kita ini emang udah ditakdirkan melarat. Mbahmu, Mbah Buyutmu, Mbah Mbah Buyutmu, semuanya melarat, Nduk!”
Aku takkan melupakan kata-kata Bapak tempo dulu saat aku berkeinginan untuk melanjutkan sekolah ke SMA. Kegigihanku akhirnya meluruhnya sifat keras Bapak. Namun, empat tahun kemudian, kata-kata yang sama meluncur lagi dari bibir Bapak, memupuskan harapanku untuk yang kedua kalinya. Takdir yang membuat kami semua melarat. Takdir yang akan membuat anak-anakku, cucuku kelak akan ikut merasakannya.
Tidak, aku tak mau seperti itu.
“Pak,” aku mengangkat kepalaku, seolah menantang Bapak bahwa ucapannya itu tidak benar. “Afri akan sekolah dengan biaya Afri sendiri, Pak.”
Sekejap mata Bapak nampak bingung, melecehkan, namun juga ada sorot bangga dalam tatap matanya itu. Perlahan tangannya itu turun dari bahuku, membenarkan kembali letak pecinya sebelum dia berbalik membelakangiku. Ucapanku itu membuat jalan Bapak sempoyongan, seolah ada beban berat yang mendudukinya.
Sebelum beliau menyibakkan tirai kamarnya, Bapak menatapku dengan tatapan nanar, “Kamu mau bercita-cita itu bagus, Nduk. Kamu bermimpi ke tempat yang jauh juga tak mengapa. Silakan kamu kuliah, tapi Bapak tak mampu memberi kamu sepeser pun. Silakan kamu pergi ke mana pun, tapi Bapak tidak bisa jamin kalau kamu tidak kecewa."
Kemudian beliau menghilang di balik tirai kamarnya, sebagai pengganti pintu yang telah lapuk bertahun lalu.
Aku berdiri tergugu, mencerna ucapan Bapak tadi. Omongan beliau sangat menohok dadaku, tetapi aku justru tersenyum mendengarnya.
Aku telah meluluhkan hati Bapak untuk kedua kalinya.
Aku tak akan kecewa, Pak, gumamku.
”Fri, mau ke mana thok kamu?” Ibu heran menatapiku yang lalu lalang tak karuan sepulang bekerja. Kusambar celengan ayam milikku dan palu milik Bapak tanpa izinnya. Sejurus kemudian, aku sudah mengenakan tas lusuh itu lagi, lengkap dengan topi caping untuk menahan panasnya matahari.
“Ke kantor Pak Ahmad, Bu!” aku bergegas pergi dan menyambar sepeda ontel yang kuparkirkan dekat sawah. Kukayuh pedalnya kuat-kuat, sambil memeluk celengan ayam di antara kedua lengan.
Aku harus cepat sampai ke kantor Pak Ahmad siang ini. Hari ini adalah pendaftaran terakhir masuk universitas. Setelah itu, aku akan memecah celengan ayam ini dan menyetorkannya ke bank sebagai uang pendaftaran.
Sesampainya di kantor kepala desa, aku mengetuk pintu ruang kerja Pak Ahmad, namun tidak ada jawaban. Kuketuk berkali-kali, tetap hasilnya nihil.
“Pak Ahmad lagi ada urusan di luar, Fri,” ujar Pak Kosim, salah satu stafnya, kebetulan melihatku. Seketika lututku lemas. Bersepeda panas-panasan di siang bolong tak bisa mengalahkan kekecewaan yang melanda diriku saat mendengar berita itu. Apakah ini pertanda? Apakah memang seharusnya semua ini tak ada?
“Tapi tadi beliau pesan, kalau ada kamu, langsung masuk aja ke dalem,” lanjutnya yang seketika membuat harapanku muncul lagi. Bayangan kekecewaan segera kutepis. Ternyata Tuhan mengizinkan!
Kepercayaan yang Pak Ahmad berikan kepadaku membuat rasa semangatku semakin memuncak. Sebentar lagi aku akan melanjutkan sekolah! Jakarta, kau akan kedatangan penghuni baru! Sambil menunggu komputer menyala, aku duduk membayangkan betapa nikmatnya dapat mengenyam bangku sekolah lagi setelah setahun ini hal itu terlupakan. Bukan itu saja, bayangan kota besar langsung menari-nari dalam benakku. Kota besar dan orang besar. Aku yakin, orang-orang besar yang tinggal di sana pasti pernah memperoleh pendidikan yang sama dengan yang aku perjuangkan sekarang. Dan untuk menjadi seperti mereka dibutuhkan usaha yang keras. Aku mengingatkan pada diri sendiri, bahwa semua ini hanyalah sebuah awal . . .
Tanpa bisa menunggu, jari-jariku sudah gatal memainkan kursor di komputer Pak Ahmad, mencari-cari nama jurusan yang sudah aku dambakan semenjak dahulu.
Teknologi Pangan.
Teknik Industri Pertanian.
Bapak. Nama itu berputar-putar dalam otakku ketika akhirnya aku mengeklik kedua jurusan dambaan itu. Sesungguhnya nama Bapak-lah satu-satunya motivasiku selama ini mengapa aku sampai membating tulang demi bersekolah. Alat-alat pertanian Bapak yang berpuluh tahun ini Bapak gunakan tak mampu mengolah sawah kami secanggih mesin-mesin modern. Hanya bermodalkan keringat, tenaga, dan keyakinan diri, sampai berpuluh tahun lamanya Bapak bertahan menjadi seorang petani. Seorang petani yang hanya mampu menghidupi anak istrinya selama puluhan tahun ini. Kata Bapak, kami ini adalah korban sistem feodal. Sistem yang membunuh rakyatnya perlahan-lahan dengan keterpurukan. Memiliki tanah, hanya sedikit. Memiliki rumah, kecil. Memiliki uang, hanya cukup untuk mengenyangkan perut anak istri.
Terima kasih. Nomor ujian Anda adalah 2781781B. Silakan melakukan pembayaran pendaftaran sebesar Rp500.000,00 melalui bank ABC dengan nomor rekening 9234019x.
Napasku tertahan. Berhasil. Segera kuraih celengan ayamku dan kupalu dengan kuat sehingga isinya berhamburan. Uang receh yang bertumpuk menyebar ke penjuru arah, membuat kantor Pak Ahmad seketika berantakan.
Kuhitung selembar demi selembar uang yang susah payah kutabung selama setahun ini, berharap lembaran ini akan menjadi pembuka jalan untukku ke depan. Untuk keluar dari sistem yang mematikan kami puluhan tahun lamanya. Aku akan menjadi awal. Aku akan menjadi pembuka jalan agar anak-anakku nanti tak perlu merasakan kepedihan yang sama seperti yang kurasakan.
Koin terakhir berhasil kukumpulkan.
Jumlahnya Rp499.000,00.
Hatiku tertohok. Dadaku sakit. Seribu. Apakah ada koin yang terlewat? Lembaran yang terlewat? Tidak, tidak ada. Aku sudah memastikan bahwa ruangan Pak Ahmad ini sudah bersih dari ceceran uang receh.
Tumpukan uang itu bergetar dalam genggamanku. Harus kucari ke mana uang seribu itu? Meminjam pada Pak Kosim? Atau Pak Ahmad? Atau . . . Bapak sekalian? Aku langsung teringat dan kembali tertampar oleh ucapan Bapak malam itu,
“Silakan kamu kuliah, tapi Bapak tak mampu memberi kamu sepeser pun.”
Mungkin . . . mungkin itu memang benar. Mungkin semua ini memang pertanda. Pesan Bapak dulu. Perginya Pak Ahmad. Uang yang tak mencukupkan. Semuanya memang pertanda bahwa perjuanganku memang harus terhenti sampai di sini.
Mungkin aku harus mencobanya lagi tahun depan, tahun depannya lagi, atau depannya lagi. Kalau tidak, mungkin aku harus menunggu satu generasi lagi untuk keluar dari sistem terkutuk ini. Kalau gagal, coba generasi berikutnya lagi. Tak mengapa, setidaknya aku telah bertahan sampai di titik ini.
Sayang, aku mau kuliah, tapi uangku kurang seribu.
Saturday 14 July 2012
Lukisan Hujan & Putri Hujan dan Ksatria Malam oleh Sitta Karina
Meski sudah lama diterbitkan, saya baru sekali membaca kedua buku ini beberapa waktu lalu. Saya telat menyadari kalau buku ini sempat booming pada zamannya, dan saat saya mencarinya ke toko buku ternyata sudah susah sekali didapat. Untungnya saya dapat membeli buku ini secara online ke penerbitnya langsung dengan harga yang miring pula. Syukurlah :)
Lukisan Hujan
Sebagai noverl pertama Sitta Karina, Lukisan Hujan ini masih nampak "canggung" dalam kata-kata dibandingkan novel-novelnya yang lain. Saya--atau hanya saya saja?--menyadari ada beberapa penggunaan kalimat yang menurut saya agak kurang pas. Misalnya, penggunaan kata-kata formal dalam percakapan ke sesama anak muda (karena sesungguhnya saya tidak pernah melakukannya :p) atau penggunaan kata "saya" ke sesama teman. Terbaca agak sedikit aneh di mata saya.
Untuk konflik, Sitta Karina sukses membuat cerita ini menjadi penuh konflik. Buku ini tidak dibawa naik (konflik) kemudian turun (resolusi), melainkan naik, turun, naik, kemudian turun lagi. Cukup membuat saya gemas karena permasalahan seakan tidak ada habisnya, tetapi itulah bumbu yang membuat buku ini menjadi sebuah page turner.
Menurut saya, cerita ini "remaja" banget dan tetap bisa saya nikmati di usia saya yang sudah bukan berada di usia remaja lagi (wow, I admit it!). Konfliknya tipikal yang sering remaja Indonesia alami. Jatuh cinta, patah hati, bertepuk sebelah tangan, sampai berantem dengan sahabat sendiri. Namun, ada beberapa hal yang membuat saya juga sedikit terganggu; yaitu bumbu-bumbu tentang kehidupan jetset dan kehidupan glamor yang menurut saya porsinya besar juga. Maybe it is only me, tapi saya hidup secara biasa saja dan merasa semua itu terlalu jauh dari kehidupan saya. Hidup dikelilingi manusia-manusia socialite Jakarta, berteman dengan para artis, model, atau dengan mudahnya bolak-balik ke luar negeri, kok di novel ini terdengar semudah itu ya :)))
Sinopsis
Sisy baru saja pindah ke perumahan Bintaro Lakeside. Diaz baru saja putus dari mantannya, Anggia, dan masih belum bisa melupakannya.
Sisy dan Diaz memiliki sifat yang sangat bertolak belakang. Sisy adalah anak yang ceria dan terlalu "polos" sampai-sampai dia sering terjebak masalah karena sikap "terlalu percaya sama orang lain"nya itu. Sementara itu, Diaz adalah seorang ice prince yang hidup sederhana di tengah keluarga Hanafiah--keluarga elit Jakarta yang memiliki perusahaan di mana-mana. Sikap Diaz yang tertutup membuatnya terkadang susah ditebak dan bagi beberapa orang boring karena sikapnya yang terlalu serius.
Ketika bertemu dengan Sisy, pertengkaran kerap terjadi di antara mereka. Adu mulut dan tarik urat sudah biasa terjadi kalau mereka sedang berbeda pendapat. Namun, lama-kelamaan hal tersebut justru menjadi pembuka jalan bagi sifat Diaz yang mulai terbuka. Diaz tidak lagi setertutup dulu karena Sisy bisa membawa Diaz menjadi lebih santai dalam kehidupannya.
Dan ketika pertemanan dan hubungan abang-adik saja mulai tak lagi cukup, Sisy dan Diaz mencoba melangkah lebih maju dalam hubungan mereka menjadi... sepasang kekasih.
Tapi semua tak berakhir sampai di situ saja. Banyak aral melintang yang harus mereka hadapi dalam mempertahankan hubungan itu.
Putri Hujan dan Ksatria Malam
Dari segi cerita juga sebenarnya standar dan "remaja" banget. Bagaimana Diaz menjemput cinta lamanya di San Fransisco dan tentunya, harus melalui banyak rintangan yang tidak mudah. Tapi bagi saya, kok bumbu-bumbu yang ditambahkan agak terkesan "drama" banget ya. Bagaimana mereka kenal dengan sebuah keluarga Jepang yang ternyata kenalannya si ini, yang ternyata sepupunya si ini, dan ternyata memiliki masa lalu pahit dengan si itu. Lalu berkenalan dengan seorang keluarga bangsawan Austria yang sangat terkenal dan juga memiliki kekayaan di mana-mana. Kayaknya dunia mereka benar-benar sangat sempit dan sangat "wow" sekali :) Selain itu juga, tentu saja dunia dan kehidupan glamor yang nampaknya sangat mudah untuk melakukan apa saja. Entahlah, tapi hidup yang seperti itu not my kind of thing, jadi agak susah untuk menikmatinya di bagian situ :)
But overall, dari segi alur saya salut dengan Sitta Karina. Sama seperti buku sebelumnya, it truly is a page turner.
Lukisan Hujan
 |
| Image Link |
Untuk konflik, Sitta Karina sukses membuat cerita ini menjadi penuh konflik. Buku ini tidak dibawa naik (konflik) kemudian turun (resolusi), melainkan naik, turun, naik, kemudian turun lagi. Cukup membuat saya gemas karena permasalahan seakan tidak ada habisnya, tetapi itulah bumbu yang membuat buku ini menjadi sebuah page turner.
Menurut saya, cerita ini "remaja" banget dan tetap bisa saya nikmati di usia saya yang sudah bukan berada di usia remaja lagi (wow, I admit it!). Konfliknya tipikal yang sering remaja Indonesia alami. Jatuh cinta, patah hati, bertepuk sebelah tangan, sampai berantem dengan sahabat sendiri. Namun, ada beberapa hal yang membuat saya juga sedikit terganggu; yaitu bumbu-bumbu tentang kehidupan jetset dan kehidupan glamor yang menurut saya porsinya besar juga. Maybe it is only me, tapi saya hidup secara biasa saja dan merasa semua itu terlalu jauh dari kehidupan saya. Hidup dikelilingi manusia-manusia socialite Jakarta, berteman dengan para artis, model, atau dengan mudahnya bolak-balik ke luar negeri, kok di novel ini terdengar semudah itu ya :)))
Sinopsis
Sisy baru saja pindah ke perumahan Bintaro Lakeside. Diaz baru saja putus dari mantannya, Anggia, dan masih belum bisa melupakannya.
Ketika bertemu dengan Sisy, pertengkaran kerap terjadi di antara mereka. Adu mulut dan tarik urat sudah biasa terjadi kalau mereka sedang berbeda pendapat. Namun, lama-kelamaan hal tersebut justru menjadi pembuka jalan bagi sifat Diaz yang mulai terbuka. Diaz tidak lagi setertutup dulu karena Sisy bisa membawa Diaz menjadi lebih santai dalam kehidupannya.
Dan ketika pertemanan dan hubungan abang-adik saja mulai tak lagi cukup, Sisy dan Diaz mencoba melangkah lebih maju dalam hubungan mereka menjadi... sepasang kekasih.
Tapi semua tak berakhir sampai di situ saja. Banyak aral melintang yang harus mereka hadapi dalam mempertahankan hubungan itu.
Putri Hujan dan Ksatria Malam
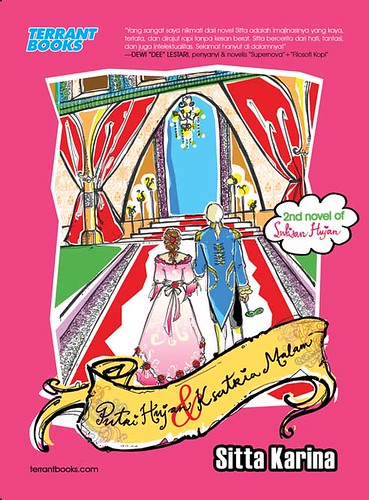 |
| Image Link |
Saat baca buku sekuelnya, saya udah lumayan bisa menikmati gaya penulisannya Sitta Karina. Much better than the previous one :)
Pertama, dari segi bahasa oke. Kedua, dari segi setting juga keren. Sitta Karina sukses menggambarkan latar setting yang sangat riil. Ketiga, saya salut akan ketotalannya dalam pengetahuan yang dimilikinya. Sitta Karina seolah-olah menguasai seluruh ilmu dalam Aikido, sastra Jepang, bahkan sampai dunia bisnis yang sangat belibet. Meskipun saya nggak ngerti, tapi saya yakin semua itu harus dilalui oleh riset yang sangat panjang.
Dari segi cerita juga sebenarnya standar dan "remaja" banget. Bagaimana Diaz menjemput cinta lamanya di San Fransisco dan tentunya, harus melalui banyak rintangan yang tidak mudah. Tapi bagi saya, kok bumbu-bumbu yang ditambahkan agak terkesan "drama" banget ya. Bagaimana mereka kenal dengan sebuah keluarga Jepang yang ternyata kenalannya si ini, yang ternyata sepupunya si ini, dan ternyata memiliki masa lalu pahit dengan si itu. Lalu berkenalan dengan seorang keluarga bangsawan Austria yang sangat terkenal dan juga memiliki kekayaan di mana-mana. Kayaknya dunia mereka benar-benar sangat sempit dan sangat "wow" sekali :) Selain itu juga, tentu saja dunia dan kehidupan glamor yang nampaknya sangat mudah untuk melakukan apa saja. Entahlah, tapi hidup yang seperti itu not my kind of thing, jadi agak susah untuk menikmatinya di bagian situ :)
But overall, dari segi alur saya salut dengan Sitta Karina. Sama seperti buku sebelumnya, it truly is a page turner.
Sunday 1 July 2012
A Thousand Splendid Suns by Khaled Hosseini
Setelah sukses dengan buku best selling-nya, The Kite Runner, pada tahun 2004, Khaled Hosseini kembali dengan novel barunya berjudul A Thousand Splendid Suns di tahun 2007 silam. Cukup lama, namun penggemar buku-buku historical fiction karyanya selalu dinanti dan memiliki tempat tersendiri di hati para penggemarnya.
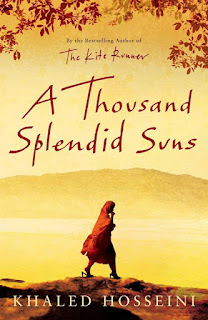
He is one of the best male author of all time. Dalam A Thousand Splendid Suns, Hosseini lebih mengupas sisi sejarah kelam Afghanistan di bawah pemerintahan Soviet dan Taliban dibandingkan dalam novel terdahulunya. Penderitaan yang tergambar sangat riil dan menciptakan sensasi tersendiri ketika membacanya. Kesakitan yang sama, kebencian yang sama seperti yang mereka rasakan pada saat itu. Bagaimana jiwa-jiwa tak bersalah dibunuh dan disiksa tanpa ampun dan bagaimana rakyat yang bertahan hidup dalam ancaman.
Hosseini juga mengupas sisi kehidupan wanita Afghanistan yang selama ini menjadi misteri. Bagaimana dulu wanita diperlakukan dalam rumah tangga, dan bagaimana anak-anak perempuan dipaksa berhenti sekolah dan menikah pada usia belia. Wanita-wanita tidak diperbolehkan keluar rumah; kehidupan mereka hanyalah terbatas oleh pagar dan dinding di sekelilingnya. Bila mereka harus keluar rumah, mereka diwajibkan memakai burqa dan wajib ditemani oleh mahramnya--wanita sama sekali tidak diperkenankan berkeliaran di jalanan seorang sendiri. Wanita dijaga sedemikian rupa, namun juga pada satu sisi lain mereka hanya dijadikan objek dan benda tak berperasaan, sebagai sasaran kekerasan oleh suaminya.
Di balik penderitaan dan kesakitan yang tercipta, Hosseini membubuhi bumbu lain yang membuat novel ini nampak sangat touching; bahwa di dunia yang tak bersahabat, di tengah kehidupan yang penuh oleh pembunuhan, pengeboman, dan siksaan, every single little pleasure may become one of the great happiness. Love, friendship, still live in the hearts of people who hope...
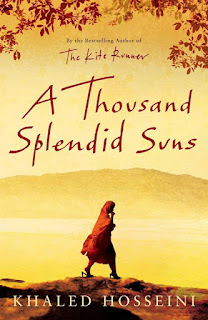
He is one of the best male author of all time. Dalam A Thousand Splendid Suns, Hosseini lebih mengupas sisi sejarah kelam Afghanistan di bawah pemerintahan Soviet dan Taliban dibandingkan dalam novel terdahulunya. Penderitaan yang tergambar sangat riil dan menciptakan sensasi tersendiri ketika membacanya. Kesakitan yang sama, kebencian yang sama seperti yang mereka rasakan pada saat itu. Bagaimana jiwa-jiwa tak bersalah dibunuh dan disiksa tanpa ampun dan bagaimana rakyat yang bertahan hidup dalam ancaman.
Hosseini juga mengupas sisi kehidupan wanita Afghanistan yang selama ini menjadi misteri. Bagaimana dulu wanita diperlakukan dalam rumah tangga, dan bagaimana anak-anak perempuan dipaksa berhenti sekolah dan menikah pada usia belia. Wanita-wanita tidak diperbolehkan keluar rumah; kehidupan mereka hanyalah terbatas oleh pagar dan dinding di sekelilingnya. Bila mereka harus keluar rumah, mereka diwajibkan memakai burqa dan wajib ditemani oleh mahramnya--wanita sama sekali tidak diperkenankan berkeliaran di jalanan seorang sendiri. Wanita dijaga sedemikian rupa, namun juga pada satu sisi lain mereka hanya dijadikan objek dan benda tak berperasaan, sebagai sasaran kekerasan oleh suaminya.
Monday 25 June 2012
Bingkai Imaji
"Kampus kita Rin, kampus kita itu cuma menjadi bingkai
imaji yang mengurung kita dari kehidupan luar. Sadar gak sih kamu Rin, kalau
kampus itu banyak dihuni oleh orang-orang yang berdaya, sementara yang tak
berdaya terlupakan di balik bingkai itu. Kita seolah-olah nggak pernah
dihadapkan oleh kenyataan yang sesungguhnya, bahwa rakyat Indonesia itu gak
semuanya seperti mereka . . . maksudku,
kalian.”
That paragraph above is the excerpt of a short story titled Bingkai Imaji. I wrote this story and sent it to Olimpiade Ilmiah Mahasiswa FIB UI .
This story was written based on my observation toward university students, especially in big cities, like Depok or Jakarta. I think there are many things that we should concern and think critically about campus life; not only the academic life, but also the other aspects. I took one of the example of how a campus could be the "stage" of showing off your economy status. The pride of driving cars to campus, wearing branded clothes, or competing to have the newest and more sophisticated gadget are the "usual" things to see. They forget that, behind that gate, outside those walls, there are so many mouths longing for food, so many men trying to find shelter, and so many children trying to survive by knocking your car windows...
You could agree with that, or you could deny it. That's what critics do.
Anyway, I'm not trying to show off, but this short story became the big 10 of Lomba Cerpen dan Puisi OIM FIB UI 2012. And this story was compiled into an Ebook that could be downloaded freely. Here's the link and you could give me your feedback after reading the full version of it. Thank you :)
That paragraph above is the excerpt of a short story titled Bingkai Imaji. I wrote this story and sent it to Olimpiade Ilmiah Mahasiswa FIB UI .
This story was written based on my observation toward university students, especially in big cities, like Depok or Jakarta. I think there are many things that we should concern and think critically about campus life; not only the academic life, but also the other aspects. I took one of the example of how a campus could be the "stage" of showing off your economy status. The pride of driving cars to campus, wearing branded clothes, or competing to have the newest and more sophisticated gadget are the "usual" things to see. They forget that, behind that gate, outside those walls, there are so many mouths longing for food, so many men trying to find shelter, and so many children trying to survive by knocking your car windows...
You could agree with that, or you could deny it. That's what critics do.
Anyway, I'm not trying to show off, but this short story became the big 10 of Lomba Cerpen dan Puisi OIM FIB UI 2012. And this story was compiled into an Ebook that could be downloaded freely. Here's the link and you could give me your feedback after reading the full version of it. Thank you :)
Saturday 16 June 2012
The Help oleh Kathryn Stockett
Namun, lama-kelamaan saya jadi menemukan kecintaan tersendiri terhadap buku-buku ber-genre ini. Saya selalu salut oleh para penulis yang "berani" mengusung genre ini. Memunculkan latar belakang sejarah dan isu yang berkembang--bahkan di zaman saat mereka sendiri belum lahir--pasti merupakan pekerjaan berat yang membutuhkan riset yang tak sedikit.
The Help salah satunya.
Buku ini mengisahkan tentang tiga orang perempuan yang hidup pada tahun '60-an di Amerika Serikat, pada saat rasisme masih menjadi isu sentral. Ada pemisahan yang jelas antara mereka yang berkulit putih dan keturunan Negro di negeri itu, terutama di negara bagian Mississippi. Yang berkulit putih distereotipkan bahwa mereka yang berada dalam hierarki tertinggi, sementara para Negro hanya menjadi kaum pekerja atau buruh dengan kondisi sosial dan ekonomi yang menyedihkan. Pemisahan antara rumah sakit, lingkungan tempat tinggal, hingga sekolah masih sangat terasa. Bahwa mereka yang berkulit hitam di"haram"kan untuk memakai fasilitas yang sama dengan mereka yang berkulit putih.
Ironisnya, wanita-wanita yang berasal dari kelas ekonomi dan sosial menengah ke atas (which are, the Whites), kebanyakan dari mereka merupakan pekerja sosial. Mereka mengirimkan donasi atas barang-barang dan makanan kepada mereka yang kelaparan di Afrika, sementara mereka yang tinggal dekat sekali dengan mereka diperlakukan selayaknya budak.
Eugenia "Skeeter" Phelan dapat mencium bau ke"tidaknormal"an ini selulusnya dari universitas. Ditambah lagi, Constantine, pengasuhnya semenjak bayi, menghilang entah kemana dan tak ada seorang pun yang mau membuka mulut untuk menjelaskannya. Bagi dia, Constantine itu lebih dari sekedar seorang pengasuh atau pembantu (The Help). Baginya, Constantine merupakan sosok ibu kedua yang menyayanginya dan menanamkan nilai-nilai kebaikan untuknya.
Berangkat dari sana, Skeeter memutuskan untuk membuat suatu perubahan dari sebuah hal kecil: melihat perspektif baru tentang isu the Whites vs Colored dari perspektif mereka yang berada dalam kategori subordinat. Yaitu para orang-orang berkulit hitam. Dari kalangan pekerja rumah tangga. Skeeter menulis sebuah buku yang berjudul Help, sebagai representasi "ini loh keadaan antara kulit putih dan kulit hitam di Mississippi tuh gini..." dan membuka pandangan masyarakat akan kenyataan yang ada. Tentu, sepanjang perjalanan penulisan buku itu, banyak pahit manis dan jatuh bangun Skeeter dan kedua sahabat kulit hitamnya yang membantu sepanjang penulisan buku, Abeileen dan Minny. Bekerja secara diam-diam, dimusuhi oleh teman-temannya, hingga ancaman maut yang menghadang.
Tentu, dalam hal itu bukan hanya hal-hal buruk saja yang disampaikan. Banyak kisah indah persahabatan yang dikisahkan antara mereka yang berkulit putih dan berkulit hitam. Banyak kisah mengharukan dalam menyatukan perbedaan-perbedaan itu yang menunjukkan bahwa they can change the condition. And sure, they can.
Wednesday 13 June 2012
Life in the Form of Fiction
"The pain increases the bliss."
The Cookie Club
"Don't keep fighting battles that are already lost."
One Day
"Bad things happen to good people."
Shooting Kabul
"When you get old and look back on your life, it's not the things you did that you regret, it's all the things that you didn't do that come back to haunt you."
Mum's the Word
"You could make something amazing out of something awful."
Last Little Blue Envelope
"Sometimes life leaves you without directions, without guideposts, or signs. When this happens, you just have to pick a direction and run like hell."
13 Little Blue Envelopes
"What is important cannot be seen."
The Little Prince
"As we turn toward the future, let us not ever forget our past, but learn what we can from it. We must not let the memories be a burden to us, but a joyous reminder for our past blessings."
Change of Heart
"It's scary how powerful hate can be."
Something Like Fate
"Chemistry could sparkle in the most surprising places and between the most unlikely people."
Love in Headscarf
"I love you because the entire universe conspired to help me find you."
The Alchemist
"Anyone who ever gave you confidence, you owe them a lot."
Breakfast at Tiffany's
"A boy who can't stand up for himself became a man who can't stand up to anything."
The Kite Runner
Saturday 5 May 2012
Emily Giffin and Her Four-Star Novels

Raise your hand if you're (also) the big fan of Emily Giffin! Everyone who knows the movie Something Borrowed must know that this movie is based on best selling novel with the same title. And who doesn't know the author? For those who have watched this movie I recommend you to also read the novel. NO, to read all Emily Giffin's novels!
To me, she's the best American chicklit author so far. I love her way of describing things and developing characters. If we take a look to the plot, it might be some kind of ordinary. Urban life, adultery, breaking up, and family conflicts. All those kinds are ordinary things. However, there's something different in her writing style. She develops these "ordinary" things into something different, something fresh and new that will never make the readers bored. What makes me really fall in love with her writings is the unexpected ending. From her 5 novels that I read, not even one book that I could guess how the ending is. This what makes me stick into these books until the ending.
In addition, the characters in these novels are also related. For example, Rachel and Dexter are the main characters of Something Borrowed. Darcy and Ethan, Rachel's best friends, are the main characters of Something Blue. Claudia, Ethan colleague's in the same publishing company, is the main character of Baby Proof. And Tessa, Dexter's sister, is the main characters of Heart of the Matter. This kind of relationship makes all those characters felt so real.
Inspiring? Yes, indeed. Here are some quotes that I found in her 5 novels.
Something Borrowed
"Sometimes good people do bad things."
"Have you ever been gone down a road, for down it, and wondered maybe if it wasn't what you want."
"Time heals all wounds, particularly if you pack a bunch of stuff into that time."
"When you're in love, sometimes you have to swallow your pride, and sometimes you have to fight to keep your pride. It's a balance."
"Sometimes the sameness in a friend is what you like the most about her."
"Patience is a virtue. Good things come to those who wait. Time cures all things."
"We can't help the way we feel."
"Nothing lasts forever, especially the good stuff."
Something Blue
"I marveled at how such a monumental realization can unfold in an instant and change every single thing in your life."
"The opposite love isn't hate; it's indifference."
"Happiness is the best revenge."
Baby Proof
"Sometimes it's easier to take things in small steps."
"Sometimes the timing is wrong--and sometimes you realize the heart of the matter way too late in the game."
"It's just that moving on sometimes consists of some minor setbacks along the way."
How emotions seemed so magnified when you're a child. Joy is more all-encompassing, disappointments more crushing, hope more palpable."
Love the One You're With
"Dreams sometimes--often--mean absolutely nothing."
"Everyone needs to get dumped once--that it's part of life."
"A son is a son 'til he gets a wife, but a daughter is a daughter all her life."
"There is more heartbreak in continuous disappointment that a void."
"What fool ever said that it's better to have loved and lost than to have never loved at all."
"Just because two people believe in something, however intensely, doesn't make it real."
Sunday 29 April 2012
The Book Thief by Markus Zusak
 A couple weeks ago, for the first time, I finished reading a historical fiction book titled A Book Thief. It was a kind of achievement for me :p because so many times I was assigned with my lecturer to read some historical fiction books, but I never finished them. It was such a miracle I intended to read this kind of book without being obliged.
A couple weeks ago, for the first time, I finished reading a historical fiction book titled A Book Thief. It was a kind of achievement for me :p because so many times I was assigned with my lecturer to read some historical fiction books, but I never finished them. It was such a miracle I intended to read this kind of book without being obliged.For those who want to read this book later, I suggest not to read this spoiler-contain review.
It was set in 1939, Germany, when the Nazi influence was still strong... When being a Jew became a sin... Liesel Meminger was a foster child of the Hubermanns. She was abandoned by her biological mother after the death of her brother. Up until the end of the story, she never told meeting her mother again. However, her life with the Hubermanns was much better. She was sent to school, she had a close friend, which was the boy next door, Toni (I forgot his family name).
What's the correlation between the plot of the story and the title, The Book Thief? Who actually is the book thief? Liesel is. The first time she stole a book when she was in her brother's funeral. The title of the book was A Grave Digger Handbook. It was such inappropriate for a 12-year-old (If I'm not mistaken) like her. However, her curiosity grew higher as she found this book. She was willing to learn to read, to open her world into a little wider. After that, stealing books became her habit. Liesel's stealing books was not because she was a thief or else, but because the economy of her family wasn't possible to afford her books. At the same time, reading became her only joy in this unfortunate situation.
If you ask some romance in this story, yes there was, but it was not as much as chicklit or teenlit books. As I mentioned before, Liesel became friend with her next door neighbor, Toni. From the very beginning, Toni showed the sign of being in love with Liesel. However, Liesel herself showed no interest in him. Funny thing was, Toni kept asking her to kiss him. Indeed, Liesel refused it again and again.
Sadly, the end of the book made Liesel suffered again of abandonment. Not because her foster parents left her, but because of the bombing that made them passed away. When she walked on the street in the following day, among the rubble, she found the dead body of her foster parents. And also Toni's. She cried and cried, holding and hugging his cold dead body. And in the end, she finally kissed him on the lips, tasting the cold blood of his that would never warm again...
"They say that war is death's best friend.
But I must offer you a different point of view on that one.
To me, war is like a new boss
Who expects the impossible." (The Book Thief--Markus Zusak)
Sunday 22 April 2012
Pertunjukan Teater "Goyang Penasaran"
Salimah meliuk-liukkan tubuhnya yang berkeringat disoroti warna-warni lampu panggung. Ditingkahi suara gendang, ia menghentak dengan celana ketat dan baju hitam penuh manik...
Salimah dihujat sekaligus tak henti dibicarakan. Dalam hati, setiap orang mengenangnya dengan cara yang berbeda.
(Cerpen Goyang Penasaran oleh Intan Paramadhita)
Mendengar judulnya saja membuat penasaran.
Pementasan teater "Goyang Penasaran" ini dipentaskan pada tanggal 19-20 April 2012 lalu di Salihara, Jakarta Selatan. Tiket yang dijual kurang lebih 400 lembar selama 2 hari telah sold out bahkan beberapa hari sebelum pementasan.
Berkisah tentang Salimah, seorang penyanyi dangdut di kampung, mantan murid pengajian di masjid yang dipimpin oleh Haji Ahmad. Di kampungnya Salimah dipuja sekaligus dihujat karena goyangannya yang membuat para laki-laki berzina mata.
Diangkat dari sebuah cerpen yang ditulis oleh Intan Paramadhita, pementasan Goyang Penasaran ini merefleksikan kehidupan masyarakat Indonesia di sebuah perkampungan. Dengan setting padat penduduk yang sangat "Indonesia", celetukan-celetukan khas golongan kelas menengah ke bawah, membuat kita membuka mata akan realita yang ada.
Perempuan. Gender.
Perempuan dan Gender selalu menjadi hal menarik yang dibahas. Ada apa sebenarnya dengan wanita? Ada apa sebenarnya dengan isu gender dan feminisme?
Salimah di sini diwujudkan sebagai seorang perempuan yang seductive, mampu menyihir kaum laki-laki dengan goyangan "mautnya". Para laki-laki memujanya, membicarakannya, bahkan penasaran kepadanya. Namun di balik pujaan-pujaan yang dilontarkan itu, mengandung kata-kata yang justru merendahkannya ke derajat paling rendah. Ironis.
Aku sebenarnya kurang mengerti soal isu-isu feminisme yang berkembang, apalagi kalau disuruh mengkritik. Tapi aku melihat banyak keironisan dalam diri Salimah sebagai perempuan. Salah satu hal yang membuatku merinding adalah saat Salimah sedang bergoyang di atas panggung, sementara Haji Ahmad sedang memberikan ceramah di masjid soal zina mata. Bagaimana tatapan itu dapat mengundang hal buruk yang lebih besar. Bagaimana Salimah penasaran dengan tatapan mata Haji Ahmad yang dulu dilihatnya dan ingin dilihatnya lagi sekarang...
Sayang, penonton tidak diperbolehkan mengambil gambar dan merekam selama pementasan berlangsung. Jadi mungkin agak sulit untuk memvisualisasikannya. Anyway, bagi yang ketinggalan pementasannya dan penasaran seperti apa ceritanya, bisa langsung beli bukunya di Salihara. Edisi terbatas!
Oh iya, ini ada link trailernya kalau masih penasaran juga.
Selamat penasaran!
Sayang, penonton tidak diperbolehkan mengambil gambar dan merekam selama pementasan berlangsung. Jadi mungkin agak sulit untuk memvisualisasikannya. Anyway, bagi yang ketinggalan pementasannya dan penasaran seperti apa ceritanya, bisa langsung beli bukunya di Salihara. Edisi terbatas!
Oh iya, ini ada link trailernya kalau masih penasaran juga.
Selamat penasaran!
Sunday 11 March 2012
"Membaca" Afghanistan
Kali ini aku akan membahas tentang buku-buku yang bertemakan negeri Afghanistan. Yap! Afghanistan. Negeri di Timur Tengah yang sarat akan konflik dan peperangan. Dan cerita-cerita dalam buku ini merefleksikan keadaan negeri tersebut melalui media kalimat dan kata-kata, membawa kita seolah-olah ikut ke dalamnya.
The Kite Runner
"In the end, the world always wins. That's just the way of things."
"Sad stories make good books."
Siapa yang tidak tahu buku bestseller ini? Buku ini merupakan buku pertama berbahasa Inggris yang ditulis oleh seorang keturunan Afghan. Menceritakan tentang negeri Afghanistan pada masa pemerintahan Taliban dan konflik antarsuku yang terjadi. Buku ini sarat akan nilai historis, nilai moral, dan juga nilai-nilai kemanusiaan.
Selimut Debu
"Di sini semua mahal, yang murah cuma satu: nyawa manusia."
Selimut Debu adalah satu dari beberapa buku yang membuat aku nggak ingin habis membacanya. Sang penulis, Agustinus Wibowo, tidak hanya melihat Afghanistan dari hanya permukaannya saja, tetapi juga ikut menyelami nilai-nilai budayanya, dan tentu saja turut dalam penderitaan masyarakatnya. Pengalamannya menjelajahi berbagai kota di Afghanistan membuat aku berdecak kagum; ternyata ada banyak hal yang tidak aku ketahui. Tentang surga yang tenang di tengah-tengah badai perang. Tentang berita pengeboman yang sudah menjadi makanan sehari-hari dan hanya menjadi angin lalu tak lama setelah ditayangkan. Tentang wanita-wanita Afghan yang dihormati sedemikian rupa hingga menyebut namanya saja menjadi sebuah bentuk penghinaan... Afghanistan dan misteri, mungkin itu memang sebuah padanan kata yang pas.
Shooting Kabul
"Bad things happen to good people."
Tinggal di sebuah negara superpower di saat negaranya berada dalam keadaan darurat mungkin menjadi jalan terbaik yang dipilih oleh keluarga Fadi, tokoh utama ini. Namun, bagaimana kalau ternyata salah satu anggota keluarga mereka 'tertinggal' di malam saat mereka 'kabur'? Jalan yang ditempuh menjadi sebuah simalakama. Keluarga Fadi harus tetap melanjutkan perjalanan apabila tidak ingin ditangkap oleh Taliban. Namun pergi dengan meninggalkan anggota keluarganya yang terkecil di tengah negara perang sendirian, di bawah rezim otoriter? Fadi memiliki cara sendiri untuk membawa adiknya kembali pulang bertemu keluarganya.
The Kite Runner
"In the end, the world always wins. That's just the way of things."
"Sad stories make good books."
Siapa yang tidak tahu buku bestseller ini? Buku ini merupakan buku pertama berbahasa Inggris yang ditulis oleh seorang keturunan Afghan. Menceritakan tentang negeri Afghanistan pada masa pemerintahan Taliban dan konflik antarsuku yang terjadi. Buku ini sarat akan nilai historis, nilai moral, dan juga nilai-nilai kemanusiaan.
Selimut Debu
"Di sini semua mahal, yang murah cuma satu: nyawa manusia."
Selimut Debu adalah satu dari beberapa buku yang membuat aku nggak ingin habis membacanya. Sang penulis, Agustinus Wibowo, tidak hanya melihat Afghanistan dari hanya permukaannya saja, tetapi juga ikut menyelami nilai-nilai budayanya, dan tentu saja turut dalam penderitaan masyarakatnya. Pengalamannya menjelajahi berbagai kota di Afghanistan membuat aku berdecak kagum; ternyata ada banyak hal yang tidak aku ketahui. Tentang surga yang tenang di tengah-tengah badai perang. Tentang berita pengeboman yang sudah menjadi makanan sehari-hari dan hanya menjadi angin lalu tak lama setelah ditayangkan. Tentang wanita-wanita Afghan yang dihormati sedemikian rupa hingga menyebut namanya saja menjadi sebuah bentuk penghinaan... Afghanistan dan misteri, mungkin itu memang sebuah padanan kata yang pas.
Shooting Kabul
"Bad things happen to good people."
Tinggal di sebuah negara superpower di saat negaranya berada dalam keadaan darurat mungkin menjadi jalan terbaik yang dipilih oleh keluarga Fadi, tokoh utama ini. Namun, bagaimana kalau ternyata salah satu anggota keluarga mereka 'tertinggal' di malam saat mereka 'kabur'? Jalan yang ditempuh menjadi sebuah simalakama. Keluarga Fadi harus tetap melanjutkan perjalanan apabila tidak ingin ditangkap oleh Taliban. Namun pergi dengan meninggalkan anggota keluarganya yang terkecil di tengah negara perang sendirian, di bawah rezim otoriter? Fadi memiliki cara sendiri untuk membawa adiknya kembali pulang bertemu keluarganya.
Friday 9 March 2012
Are We Happy?
Di beberapa postingan sebelumnya aku sudah sempat membahas tentang sebuah buku berjudul The Geography of Bliss. Dalam buku ini memang Indonesia tidak masuk di salah satu chapternya, tapi aku kaget saat awal membaca bagian Introduction-nya, ternyata Indonesia sempat di-mention dalam buku ini. Ingin tahu apa isinya?
"As a foreign correspondent for National Public Radio, I traveled to places such as Iraq, Afghanistan, and Indonesia: unhappy places." (Eric Weiner, The Geography of Bliss, 2008, p. 2)
Sambil membacanya, aku ikut bertanya dan merenung dalam hati, is it? Apakah benar Indonesia tempat yang tidak menyenangkan seperti yang disebutkan dalam buku itu? Aku mengingat-ingat kejadian dalam hidupku. Dikelilingi sebuah keluarga yang menyayangiku, bertemu teman-teman yang gila dan menyenangkan, kuliah di salah satu universitas (yang katanya) terbaik se-Indonesia. Canda, tawa, bahagia, syukur, rasanya tak pernah ada habisnya dalam hidupku. Apakah semua itu termasuk ke dalam kriteria 'unhappy' seperti yang dikatakan?
Aku tak tahu parameter apa yang digunakan oleh sang penulis dalam mendeskripsikan bahwa Indonesia itu adalah sebuah 'unhappy place', apalagi kalau disandingkan oleh Iraq dan Afghanistan. Hey, we aren't a war country, are we?
Membaca kalimat itu jadi membuat aku teringat oleh buku yang kubaca beberapa tahun lalu. Aku lupa apa bukunya dan siapa penulisnya, yang pasti sang penulisnya adalah orang asing yang datang ke Indonesia. Kurang lebih dia mengatakan begini; dia telah mengunjungi negara-negara lain yang punya masyarakat miskin. Dan mereka itu benar-benar nampak miserable. Dalam artian, sudah tidak ada uang, tidak ada kebahagiaan, dan seolah-olah semangat hidup menguap begitu saja. Tapi begitu dia datang ke Indonesia, meskipun dia melihat masyarakat miskin yang hidupnya menyedihkan, dia bisa merasakan perbedaan. Di Indonesia, meskipun miskin, orang-orangnya masih banyak yang tersenyum. Anak-anaknya masih bisa menikmati masa kecil, bermain di luar bersama teman-temannya, dan yang jelas mereka nampak bahagia.
Saat aku kembali pada buku yang kubaca dan memikirkan ulang, aku jadi penasaran tahun berapa penulisnya menuliskan buku ini. Disebutkan bahwa bukunya diterbitkan pada tahun 2008, dan aku langsung penasaran dengan apa yang terjadi di Indonesia pada tahun itu.
Hukuman mati Amrozi cs. dilaksanakan pada tahun 2008. Tepat saat buku ini diterbitkan. Aku berasumsi bahwa dia menulis buku ini beberapa tahun sebelumnya karena membutuhkan riset yang cukup panjang, dan aku menelusuri lagi apa yang terjadi di Indonesia pada tahun sebelum itu. Bom Bali II pada tahun 2005. Tsunami Aceh tahun 2004. Pengeboman Kedubes Australia tahun 2004. Pengeboman hotel J.W. Marriot tahun 2003. Bom Bali I tahun 2002.
Aku tersenyum maklum. Pantas saja penulisnya sampai hati menuliskan Indonesia sebagai 'unhappy place'. Karena kalau dilihat, kisaran tahun-tahun itu memang sedang masanya Indonesia menjadi 'sarang' terorisme. Pengeboman terjadi di mana-mana, ditambah bencana alam yang sering melanda, termasuk Tsunami Aceh yang menewaskan ribuan nyawa.
Pertanyaannya sekarang, di balik statement itu, are we really happy?
"As a foreign correspondent for National Public Radio, I traveled to places such as Iraq, Afghanistan, and Indonesia: unhappy places." (Eric Weiner, The Geography of Bliss, 2008, p. 2)
Sambil membacanya, aku ikut bertanya dan merenung dalam hati, is it? Apakah benar Indonesia tempat yang tidak menyenangkan seperti yang disebutkan dalam buku itu? Aku mengingat-ingat kejadian dalam hidupku. Dikelilingi sebuah keluarga yang menyayangiku, bertemu teman-teman yang gila dan menyenangkan, kuliah di salah satu universitas (yang katanya) terbaik se-Indonesia. Canda, tawa, bahagia, syukur, rasanya tak pernah ada habisnya dalam hidupku. Apakah semua itu termasuk ke dalam kriteria 'unhappy' seperti yang dikatakan?
Aku tak tahu parameter apa yang digunakan oleh sang penulis dalam mendeskripsikan bahwa Indonesia itu adalah sebuah 'unhappy place', apalagi kalau disandingkan oleh Iraq dan Afghanistan. Hey, we aren't a war country, are we?
Membaca kalimat itu jadi membuat aku teringat oleh buku yang kubaca beberapa tahun lalu. Aku lupa apa bukunya dan siapa penulisnya, yang pasti sang penulisnya adalah orang asing yang datang ke Indonesia. Kurang lebih dia mengatakan begini; dia telah mengunjungi negara-negara lain yang punya masyarakat miskin. Dan mereka itu benar-benar nampak miserable. Dalam artian, sudah tidak ada uang, tidak ada kebahagiaan, dan seolah-olah semangat hidup menguap begitu saja. Tapi begitu dia datang ke Indonesia, meskipun dia melihat masyarakat miskin yang hidupnya menyedihkan, dia bisa merasakan perbedaan. Di Indonesia, meskipun miskin, orang-orangnya masih banyak yang tersenyum. Anak-anaknya masih bisa menikmati masa kecil, bermain di luar bersama teman-temannya, dan yang jelas mereka nampak bahagia.
Saat aku kembali pada buku yang kubaca dan memikirkan ulang, aku jadi penasaran tahun berapa penulisnya menuliskan buku ini. Disebutkan bahwa bukunya diterbitkan pada tahun 2008, dan aku langsung penasaran dengan apa yang terjadi di Indonesia pada tahun itu.
Hukuman mati Amrozi cs. dilaksanakan pada tahun 2008. Tepat saat buku ini diterbitkan. Aku berasumsi bahwa dia menulis buku ini beberapa tahun sebelumnya karena membutuhkan riset yang cukup panjang, dan aku menelusuri lagi apa yang terjadi di Indonesia pada tahun sebelum itu. Bom Bali II pada tahun 2005. Tsunami Aceh tahun 2004. Pengeboman Kedubes Australia tahun 2004. Pengeboman hotel J.W. Marriot tahun 2003. Bom Bali I tahun 2002.
Aku tersenyum maklum. Pantas saja penulisnya sampai hati menuliskan Indonesia sebagai 'unhappy place'. Karena kalau dilihat, kisaran tahun-tahun itu memang sedang masanya Indonesia menjadi 'sarang' terorisme. Pengeboman terjadi di mana-mana, ditambah bencana alam yang sering melanda, termasuk Tsunami Aceh yang menewaskan ribuan nyawa.
Pertanyaannya sekarang, di balik statement itu, are we really happy?
Kalau aku harus menjawabnya, jawabanku tentu saja ya. Apa yang bisa membuat kita tidak bahagia? Karena "saat demi saat begitu ajaib. Tanpa ditambah ide apapun, sudah begitu... sempurna." (Marina Silvia K., Back "Europe" Pack: Keliling Eropa 6 Bulan Hanya 1.000 Dollar)
Jadi, apa jawabanmu?
Saturday 3 March 2012
The Geography of Bliss oleh Eric Weiner
Buku ini aku temukan di salah satu pojok diskonan di toko buku Periplus, PIM. Cukup memuaskan harganya, 15.000 dari harga aslinya yang 80.000. Dan isinya, tentu saja lebih memuaskan.
Buku ini bukan hanya berkisah tentang traveling, mempelajari kebudayaan dan masyarakatnya saja. Tapi penulisnya menulis 'lebih' dari dari itu dalam buku ini. Dia ingin menemukan arti "kebahagiaan" yang berbeda di setiap negara yang dikunjungi. Dia berinteraksi dengan masyarakatnya, mempelajari adat istiadatnya, dan tidak lupa bagaimana mereka mendefinisikan sebuah "kebahagiaan" yang ternyata sangat beragam.
Aku sendiri sebenarnya belum selesai membaca buku ini, tapi gatal banget pengen berbagi. Di buku ini penulisnya berkisah di sepuluh negara yang berbeda. Negara-negara yang sudah aku baca ada Iceland, Qatar, Bhutan, Belanda, dan Swiss. Lucu, saat menemukan fakta baru di negara-negara tersebut yang sebelumnya tak pernah aku tahu. Misalnya di Belanda, di sana ada seorang professor yang mengadakan penelitian tentang "kebahagiaan". Disebutkan bahwa orang yang menikah lebih bahagia dibandingkan yang single, orang yang menikah dan tidak memiliki anak lebih bahagia dibandingkan yang memiliki, orang kaya lebih bahagia dari orang miskin. Lucunya, definisi kebahagiaan tersebut ternyata bisa dihitung dan distatistikan oleh angka-angka.
Berbeda lagi dengan di Qatar. Ada sebuah kutipan lucu yang dituliskan oleh sang penulis. "I read somewhere that Qatar is 98.09 percent desert. I wonder what the other 1.91 percent is. Mercedes, perhaps." Karena masyarakat Qatar pada umumnya telah memiliki kehidupan yang layak. Memiliki servants, tidak perlu bayar pajak, bahkan mereka tidak perlu convenient stores karena hidup mereka sudah convenient enough.
Intinya, buku ini adalah bacaan wajib bagi pecinta traveling atau pecinta buku traveling. Kita tidak hanya diajak melihat hal-hal yang baik dan menyenangkan saja, tetapi juga diajak untuk lebih menyelami kehidupan itu sendiri sehingga akhirnya menemukan apa arti kebahagiaan yang sebenarnya.
Buku ini bukan hanya berkisah tentang traveling, mempelajari kebudayaan dan masyarakatnya saja. Tapi penulisnya menulis 'lebih' dari dari itu dalam buku ini. Dia ingin menemukan arti "kebahagiaan" yang berbeda di setiap negara yang dikunjungi. Dia berinteraksi dengan masyarakatnya, mempelajari adat istiadatnya, dan tidak lupa bagaimana mereka mendefinisikan sebuah "kebahagiaan" yang ternyata sangat beragam.
Aku sendiri sebenarnya belum selesai membaca buku ini, tapi gatal banget pengen berbagi. Di buku ini penulisnya berkisah di sepuluh negara yang berbeda. Negara-negara yang sudah aku baca ada Iceland, Qatar, Bhutan, Belanda, dan Swiss. Lucu, saat menemukan fakta baru di negara-negara tersebut yang sebelumnya tak pernah aku tahu. Misalnya di Belanda, di sana ada seorang professor yang mengadakan penelitian tentang "kebahagiaan". Disebutkan bahwa orang yang menikah lebih bahagia dibandingkan yang single, orang yang menikah dan tidak memiliki anak lebih bahagia dibandingkan yang memiliki, orang kaya lebih bahagia dari orang miskin. Lucunya, definisi kebahagiaan tersebut ternyata bisa dihitung dan distatistikan oleh angka-angka.
Berbeda lagi dengan di Qatar. Ada sebuah kutipan lucu yang dituliskan oleh sang penulis. "I read somewhere that Qatar is 98.09 percent desert. I wonder what the other 1.91 percent is. Mercedes, perhaps." Karena masyarakat Qatar pada umumnya telah memiliki kehidupan yang layak. Memiliki servants, tidak perlu bayar pajak, bahkan mereka tidak perlu convenient stores karena hidup mereka sudah convenient enough.
Tuesday 7 February 2012
Australian Open 2012
Monday 6 February 2012
A Bunch of New Books
Udah aku ceritain kan di postingan sebelumnya kalau pulang-pulang dari Aussie aku bawa 2 koper. 1 koper itu isinya untuk baju dan oleh-oleh, dan yang satunya lagi untuk... buku. Di Chadstone, mal yang deket rumah omku itu, ada toko buku yang namanya allbooks4less. Di Indonesia, gak bakal ada toko buku yang begini, karena di sini semua harga buku dipukul rata dan hanya 5 dollar saja. Kenapa aku bilang hanya? Karena kalau dikurskan ke rupiah, buku-buku impor kayak gitu gak akan ada yang harganya sebanding dengan segitu...
 |
| 5 dollar saja! |
Buku sebagus itu--kertas foto, full color, tebalnya kebangetan, cuma 5 dollar aja di situ. Photobook sekaligus biografi The Beatles juga cuma 5 dollar. Buku A History of Britain juga... 5 dollar aja! Aku bolak-balik ke sana 2x. Yang pertama kali aku ke sana sendiri, masih agak-agak nggak percaya gitu kalau buku-buku disitu harganya 5 dollaran. Akhirnya aku 'cuma' beli 5 aja sebangai pengetes... Eh ternyata emang bener. Beberapa hari kemudian aku balik lagi ke sana, ditemenin sama sepupu aku dan sukses memboyong 7 buku lagi. Jadi total buku aku ada 12 *ketawa setan*
Nah, sebelum-sebelumnya juga aku sempet hunting buku di Monash Uni sama Melbourne Uni bookstore dan sempet beli beberapa buku dan satu kamus. Jadi totalnya semua ada 16 buku (alias satu koper penuh).
Daaan... sebelum berangkat ke Aussie juga aku udah beli beberapa buku yang belum sempet kebaca. Sekarang tinggal mikirin gimana caranya ngabisin semua buku itu @_@
Subscribe to:
Posts (Atom)



















